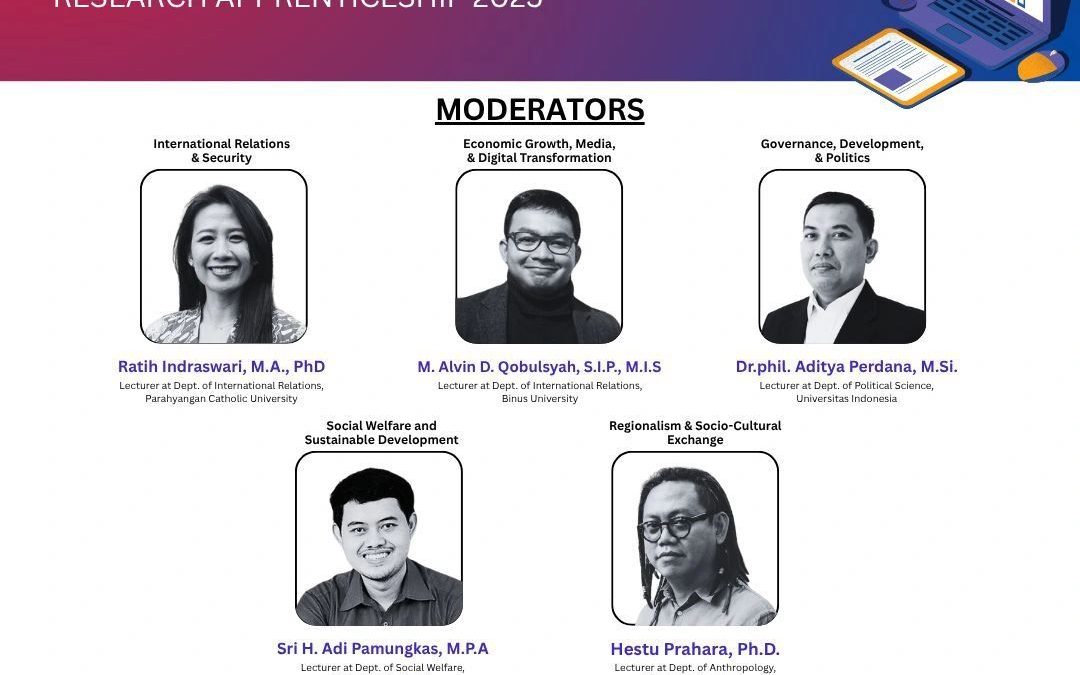Ditulis oleh Mahasiswa : Chika Amalliah Purnomo (6092201218@student.unpar.ac.id); Fauzan Fadhil Ibrahim (6092201074@student.unpar.ac.id); Viandra Virgianto (6092201128@student.unpar.ac.id); Traviata Capella P. (6092201003@student.unpar.ac.id)
Gagasan reunifikasi antara Korea Utara dan Korea Selatan telah lama menjadi salah satu isu paling sensitif di Asia Timur. Bagi masyarakat Korea, penyatuan kembali dua negara yang terpisah sejak Perang Korea bukan hanya persoalan politik, tetapi juga emosional dan historis. Namun, di balik idealisme itu, terdapat berbagai konsekuensi ekonomi dan geopolitik yang patut dipertimbangkan, terutama oleh negara-negara mitra dagang seperti Indonesia. Dari sudut pandang kepentingan perdagangan internasional Indonesia, unifikasi Korea justru berpotensi membawa lebih banyak ketidakpastian dibandingkan keuntungan. Hal ini didasari oleh beberapa pertimbangan.
Pertama Korea Selatan saat ini merupakan salah satu mitra ekonomi paling penting bagi Indonesia. Hubungan kedua negara semakin erat melalui kerangka kerja ekonomi Indonesia–Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA), yang mulai berlaku pada tahun 2023. Melalui perjanjian ini, volume perdagangan antara Indonesia dan Korea Selatan memiliki peningkatan yang cukup signifikan di beberapa barang dagang. Korea Selatan menjadi mitra dagang terbesar ketujuh Indonesia serta salah satu investor terbesar di sektor strategis seperti kendaraan listrik, manufaktur baterai, energi baru terbarukan, dan infrastruktur. Hubungan ini bersifat saling komplementer atau melengkapi, Korea Selatan unggul dalam teknologi dan modal, sementara Indonesia kaya akan sumber daya alam seperti nikel, batu bara, dan minyak sawit yang mendukung industri manufaktur Korea Selatan. Pola hubungan ini menciptakan interdependensi ekonomi yang stabil dan saling menguntungkan.
Namun, apabila unifikasi antara Korea Utara dan Korea Selatan benar-benar terjadi, kestabilan ekonomi Korea Selatan yang selama ini menjadi dasar hubungan dagang dengan Indonesia kemungkinan besar akan terguncang. Pengalaman Jerman pasca-reunifikasi tahun 1990 menunjukkan bahwa biaya integrasi wilayah dengan tingkat pembangunan ekonomi yang sangat timpang bisa sangat besar. Korea Selatan, dengan ekonomi maju dan sistem pasar yang terbuka, akan menghadapi beban fiskal yang berat untuk membangun kembali Korea Utara yang selama ini tertutup. Dalam skenario ini, besar kemungkinan bahwa Korea Selatan akan mengalihkan fokus fiskal dan politiknya ke dalam negeri untuk menstabilkan ekonomi internal. Akibatnya, investasi luar negeri, termasuk ke Indonesia, bisa berkurang secara signifikan dalam jangka pendek hingga menengah.
Kedua, bagi Indonesia, pengurangan arus investasi Korea Selatan tentu akan berdampak langsung terhadap sejumlah sektor penting. Banyak proyek kerja sama antara kedua negara, seperti pengembangan pabrik baterai di Karawang, sektor transportasi massal, serta proyek energi hijau, sangat bergantung pada modal dan teknologi Korea Selatan. Jika prioritas fiskal Seoul bergeser ke pembangunan Korea Utara, maka banyak proyek bilateral berpotensi tertunda atau bahkan dibatalkan. Kondisi ini dapat menurunkan kecepatan industrialisasi Indonesia dan memperlambat upaya pemerintah untuk membangun ekosistem kendaraan listrik nasional yang saat ini sedang digencarkan.
Ketiga, unifikasi juga berpotensi mengubah arah kebijakan perdagangan Korea. Selama ini, Korea Selatan bergantung pada impor bahan baku dari negara seperti Indonesia untuk menopang industri manufakturnya. Namun, Korea yang bersatu akan mencoba mengeksplorasi potensi sumber daya alam Korea Utara sendiri, seperti batu bara, bijih besi, dan mineral lainnya. Hal ini dapat menurunkan volume ekspor komoditas mentah Indonesia ke Korea. Dengan kata lain, unifikasi justru dapat menciptakan kondisi kompetitif baru yang tidak menguntungkan bagi posisi dagang Indonesia.
Keempat, dari sisi makroekonomi, adanya beban fiskal yang muncul akibat terjadinya proses integrasi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi kedua Korea. Pemerintah Korea Selatan harus menaikkan pajak dan mengalihkan sebagian anggaran yang dialokasikan luar negeri untuk program rehabilitasi ekonomi di wilayah utara. Situasi ini bisa menekan nilai mata uang won dan menurunkan daya beli masyarakat Korea terhadap produk impor, termasuk barang dari Indonesia. Dalam jangka pendek, hal ini akan memperburuk neraca perdagangan Indonesia terhadap Korea karena menurunnya permintaan ekspor.
Kelima, unifikasi Korea akan membawa implikasi geopolitik yang kompleks di kawasan Asia Timur. Stabilitas politik yang selama ini menopang iklim investasi di kawasan bisa terganggu, terutama jika proses unifikasi memicu ketegangan baru dengan negara-negara besar seperti Tiongkok, Jepang, atau Amerika Serikat. Ketidakpastian geopolitik ini dapat menimbulkan efek domino terhadap pasar regional dan mengganggu rantai pasok global. Indonesia, sebagai negara yang bergantung pada ekspor komoditas dan hubungan dagang lintas kawasan, tentu tidak akan luput dari dampak tersebut.
Terakhir, selain aspek ekonomi, penting juga untuk mempertimbangkan risiko sosial dan politik yang dapat muncul dari proses unifikasi. Korea Selatan akan menghadapi tantangan besar dalam menyatukan dua masyarakat dengan ideologi, sistem pendidikan, dan nilai budaya yang sangat berbeda. Ketegangan sosial yang mungkin timbul selama proses ini dapat memperlambat pemulihan ekonomi dan mengurangi stabilitas pasar domestik Korea. Dalam kondisi seperti itu, kemampuan Korea Selatan untuk mempertahankan peran ekonominya di kawasan akan melemah, yang pada akhirnya juga akan mengurangi manfaat perdagangan bagi Indonesia.
Dari seluruh pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa unifikasi Korea, meskipun diinginkan secara moral dan historis, dapat menggangu hubungan ekonomi dengan partner external, termasuk Indonesia. Oleh sebab itu, selain mengedepankan pertimbangan domestik antara kedua Korea, konsiderasi akan implikasi unifikasi terhadap hubungan dengan partner external perlu diperhatikan.